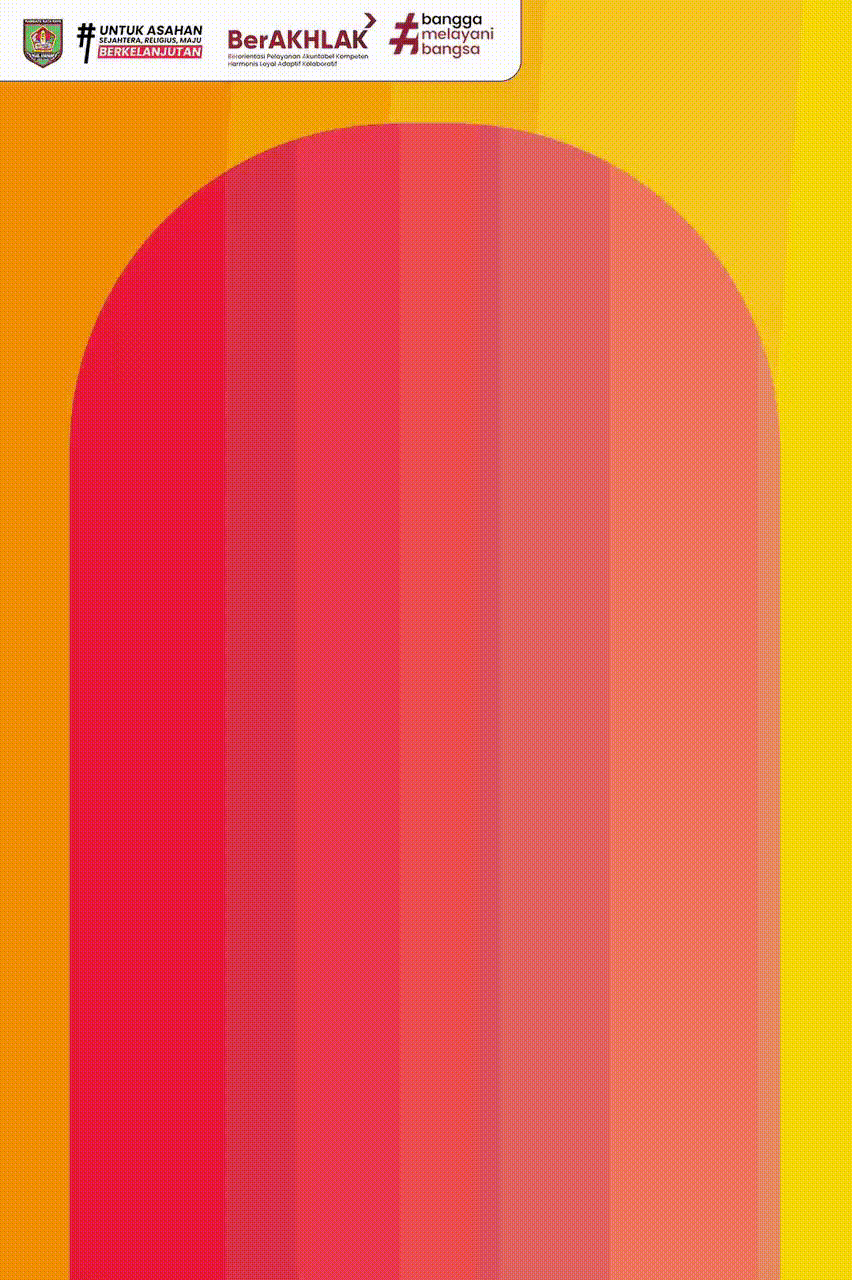Paradigma yang Terlupakan: Ketika Kemiskinan Didekati Tanpa Kesadaran Epistemik
BOLTIM – Fiko Onga melalui penelitiannya membedah lapisan terdalam Collaborative Governance dan model Pentahelix dalam pengentasan kemiskinan di Bolaang Mongondow Timur. Temuannya menunjukkan bahwa kolaborasi yang tampak formal di permukaan justru menyimpan ketimpangan partisipasi dan kekosongan kelembagaan. Merujuk pada kerangka paradigma penelitian dari Brown & Dueñas (2020), Fiko menyoroti pentingnya pergeseran dari paradigma positivistik-birokratis menuju konstruktivistik dan kritis. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan sekadar data statistik, tetapi realitas sosial yang kompleks dan perlu ditanggapi melalui pendekatan yang reflektif, partisipatif, dan berbasis kepercayaan. Perubahan regulasi dari TKPKD ke BPPK tanpa kejelasan justru menambah kerentanan.
Di balik grafik dan angka kemiskinan yang terus mengendap di sudut-sudut negeri, ada satu ironi yang jarang disadari: sering kali kita mendekati kemiskinan hanya sebagai masalah data, bukan sebagai kenyataan sosial yang hidup. Maka ketika Collaborative Governance dan Pentahelix dielu-elukan sebagai formula strategis pengentasan kemiskinan, kita perlu bertanya: dari paradigma mana kita menilai keberhasilan itu?
Sebuah infografik dari Medical Science Educator (Brown & Dueñas, 2020) menyodorkan refleksi mendalam tentang bagaimana memilih paradigma riset. Dimulai dari axiology—apa yang kita nilai—hingga epistemology—bagaimana kita membangun pengetahuan, dan methodology—bagaimana kita memperoleh dan mengolah realitas—paradigma penelitian bukan sekadar teknik. Ia adalah cermin: tentang nilai, posisi, dan niat.
Sayangnya, pendekatan terhadap pengentasan kemiskinan di banyak daerah, termasuk Bolaang Mongondow Timur, seringkali terjebak dalam paradigma positivistik-administratif. Seolah dengan menyusun RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah), menggelar rapat triwulanan, dan mendistribusikan bantuan sosial, urusan selesai. Padahal, realitas yang ditemui di lapangan begitu berbeda: masyarakat tidak tahu mengapa mereka menerima bantuan, tidak merasa terlibat, bahkan tidak tahu apa yang sedang dirancang atas nama mereka.
Dalam infografik itu, ada alternatif: paradigma konstruktivistik—yang menyatakan bahwa realitas tidak tunggal dan objektif, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial. Di sinilah letak kelemahan fatal praktik kolaborasi saat ini: ketika masyarakat hanya dijadikan objek administratif, dan bukan subjek kolaboratif.
Lebih lanjut, penelitian Anda menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat invited space, bukan claimed space. Masyarakat hanya diajak hadir saat acara, tetapi tidak pada saat keputusan dibuat. Padahal, jika kita meminjam epistemologi konstruktivistik, pengetahuan yang sah bukanlah hasil survei tunggal, melainkan hasil dari negosiasi makna antara berbagai pihak.
Paradigma critical theory juga memberi peringatan penting: ketika tata kelola tidak disadari sebagai medan kekuasaan, maka ketimpangan akan disamarkan sebagai prosedur. Transformasi dari TKPKD ke BPPK yang tidak jelas justru menciptakan kekosongan hukum dan kerapuhan koordinasi, seperti yang Anda temukan. Di sini, tata kelola bukan netral, melainkan penuh implikasi struktural.
Mengapa Ini Penting?
Karena metode—sebagaimana disebut dalam grafik—tidak netral. Pilihan antara wawancara terbuka, observasi partisipatif, atau survei tertutup tidak hanya soal teknik, tetapi soal posisi etis dan politis. Dalam studi, penggunaan wawancara mendalam dan FGD menunjukkan komitmen pada pendekatan partisipatif, tetapi sayangnya, struktur kelembagaan belum mendukung metode itu secara menyeluruh.
Maka, revisi paling mendesak bukan hanya pada format program, tetapi pada paradigma berpikir. Jika kita benar-benar ingin “mengentaskan kemiskinan”, maka kita harus berhenti memperlakukan kemiskinan sebagai objek statistik. Kita harus mulai memperlakukan kemiskinan sebagai hasil dari relasi sosial yang kompleks, yang hanya bisa dipahami dan ditangani lewat kolaborasi yang otentik—bukan yang simbolik.
Refleksi Penutup
Paradigma bukan teori abstrak. Ia adalah landasan dari setiap keputusan, setiap rumusan kebijakan, setiap desain kolaborasi. Tanpa kesadaran atas itu, kita hanya mengulang kesalahan: memerangi kemiskinan dengan logika birokrasi, bukan dengan empati sosial.
Jika Bolaang Mongondow Timur ingin menjadi model kolaboratif sejati, maka langkah awalnya bukan revisi regulasi, tetapi revolusi paradigma. (*)